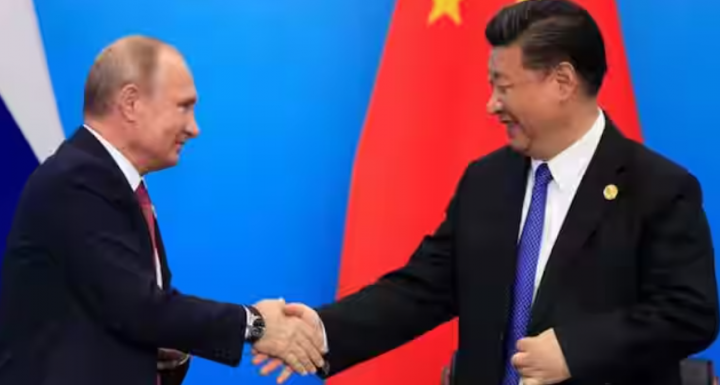Inilah Alasan Mengapa Malaysia dan Indonesia Memiliki Perbedaan Terkait Klaim Maritim di Laut Cina Selatan

RIAU24.COM - Selama dua tahun terakhir, perusahaan minyak milik negara Malaysia, Petronas, terus mengembangkan ladang gas di Laut China Selatan yang disengketakan, terlepas dari apa yang baru-baru ini digambarkan oleh sebuah think tank yang berbasis di AS sebagai “pelecehan harian” dari kapal-kapal China.
Negara tersebut tidak mau mengalah atas kepentingannya di Luconia Shoals, di mana ia mengembangkan ladang gas Kasawari yang besar – diperkirakan mengandung 3 triliun kaki kubik sumber daya gas yang dapat diperoleh kembali – dan sikapnya yang tanpa kompromi adalah tipikal pendekatannya terhadap klaim China yang tumpang tindih di perairan yang disengketakan.
Pada bulan Juni, mereka mengacak pesawat tempur ketika mendeteksi 16 jet angkut militer China terbang dekat dengan wilayah udara Malaysia tanpa pemberitahuan sebelumnya, kemudian memanggil duta besar China Ouyang Yujing untuk penjelasan.
Indonesia juga telah vokal di masa lalu tentang apa yang dilihatnya sebagai serangan China ke perairannya.
Pada 2019, ia mengajukan nota diplomatik yang menentang apa yang disebutnya perambahan kapal penangkap ikan Tiongkok ke Laut Natuna, yang diklaim Indonesia sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusifnya, tetapi bagian-bagian yang diklaim Tiongkok memiliki hak penangkapan ikan bersejarah. Indonesia bukan pihak dalam sengketa Laut China Selatan yang melibatkan China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.
Namun bagi beberapa pengamat, pendekatan Indonesia telah mengambil giliran yang hati-hati akhir-akhir ini, terutama sehubungan dengan insiden pada 31 Agustus ketika sebuah kapal survei China, Haiyang Dizhi 10, memasuki Laut Natuna Utara di dekat ladang minyak dan gas penting yang dikenal sebagai Blok Tuna.
Kapal, yang tampaknya sedang melakukan survei seismik, pergi sebentar pada bulan September dan kembali pada awal Oktober sebelum meninggalkan perairan sekitar seminggu yang lalu.
Dalam kuliah singkat di Catholic University of America di Washington pada 18 Oktober, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tampaknya mengecilkan keberadaan kapal China di perairan yang diklaim Indonesia, dengan mengatakan “kami menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna”.
Tanggapan itu membuat beberapa analis bertanya-tanya apakah nada Indonesia yang lebih berhati-hati ada hubungannya dengan ketergantungannya pada investasi China dan vaksin Covid-19.
Menurut Badan Penanaman Modal Indonesia (BKPM), China adalah investor asing terbesar kedua di Indonesia pada tahun 2020, dengan nilai USD 4,8 miliar (S$6,5 miliar). Sementara itu, perusahaan farmasi China, Sinovac dan Sinopharm, telah mengirimkan 215 juta dosis vaksin ke Indonesia, menurut Xiao Qian, Duta Besar China untuk Indonesia.
Gilang Kembara, seorang peneliti di Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang berbasis di Jakarta, mengemukakan kemungkinan alasan lain untuk nada kehati-hatian tersebut adalah kekhawatiran Indonesia bahwa masalah tersebut “berpotensi berubah menjadi pertengkaran politik eksternal yang pada gilirannya dapat meningkatkan anti- Sentimen Cina di negara ini”.
Imam Prakoso, seorang analis di Indonesia Ocean Justice Initiative, mengatakan tanggapan Indonesia terhadap Haiyang Dizhi sangat berbeda dengan pendekatannya pada tahun 2019. “Sementara kapal patroli dikirim untuk membayangi kapal itu … tidak ada nota diplomatik protes yang dikeluarkan untuk menanggapi perambahannya,” katanya.
“Bukan berarti pemerintah Indonesia meremehkan keberadaan kapal survei ini. Sebaliknya, posisi ini mungkin diambil karena prioritas Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama di tengah pandemi Covid-19.”
Bill Hayton, rekan rekanan program Asia-Pasifik di Chatham House yang berbasis di London, mengatakan Malaysia dan Indonesia melihat hubungan mereka dengan China sebagai “multifaset” dan tidak membiarkan masalah Laut China Selatan mendominasi.
Namun, dia mengatakan perhitungan relatif untuk setiap negara berbeda. “Malaysia saat ini mengebor di Laut China Selatan, dan telah mampu terus melakukannya meskipun ada gangguan dari China,” kata Hayton, penulis The South China Sea: The Struggle for Power in Asia.
“Malaysia telah mengerahkan kapal angkatan laut untuk melindungi operasinya dan tampaknya telah menerima dukungan dari angkatan laut lain juga. Indonesia tidak mengebor di area 'sensitif' saat ini dan hanya mengamati China membuat apa yang tampak seperti survei seismik komersial di dalam zona ekonomi eksklusifnya.”
Hayton mengatakan Indonesia bisa saja mengerahkan kapal angkatan laut untuk mengusir kapal China itu juga, tetapi mungkin memilih untuk menghindari konfrontasi.
“[Indonesia] tidak rugi secara material dari tindakan China tetapi perlu memperhatikan konsekuensi hukumnya,” tambah Hayton.
Namun, Zachary Abuza, Profesor studi Asia Tenggara di National War College yang berbasis di Washington, mengatakan bahwa sementara Malaysia berusaha "tidak diganggu", dia tidak yakin itu "lebih keras" daripada Indonesia.
Ironisnya, Malaysia bahkan membeli “kapal-kapal China untuk mempertahankan diri dari agresi China”, katanya. Bulan lalu, Malaysia menerima pengiriman Kapal Misi Littoral ketiga dari China. Yang keempat diharapkan akan diserahkan Desember ini. Abuza mengatakan bahwa pada akhirnya Malaysia dan Indonesia sama-sama sangat bergantung secara ekonomi pada China sehingga “tidak merasa bahwa mereka dapat melawan China dengan cara yang akan menghalangi agresi China”.
China telah menjadi investor utama Malaysia sejak 2016, menghasilkan US$4,41 miliar pada 2020. China juga telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia sejak 2009, dan menyumbang 18,6 persen dari total perdagangan tahun lalu.
“Malaysia … tidak menantang China secara langsung di depan umum,” lanjut Abuza. “Tetapi Malaysia melawan China melalui berbagai pengajuan Unclos [Konvensi PBB tentang Hukum Laut] dan dengan terus mengeksplorasi minyak, meskipun ada intimidasi China yang terang-terangan,” kata Abuza.
Salah satu contoh pengajuan ini datang pada 12 Desember 2019, ketika Malaysia mengajukan pengajuan kepada Komisi Batas Landas Kontinen untuk bagian utara Laut Cina Selatan, badan yang bertugas mengatur penerapan Unclos. Langkah itu diharapkan dapat membantu Malaysia menetapkan hak atas semua sumber daya dasar laut dan tanah di bawahnya - termasuk cadangan minyak dan gas - yang mungkin ada di daerah tersebut.
Seorang pejabat senior pemerintah Indonesia mengatakan negara itu berusaha untuk menghindari “diplomasi megafon”, menambahkan bahwa “namun, langkah-langkah telah diambil dan akan diambil secara diplomatis untuk memastikan bahwa hak-hak Indonesia tidak dilanggar”.
Pejabat itu mengatakan Indonesia sangat percaya pada implementasi Unclos dan bahwa setiap tindakan atau tanggapan dari Indonesia akan didasarkan pada konvensi. Collin Koh, seorang peneliti di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam Singapura, setuju bahwa tampaknya ada “kehati-hatian tertentu dari pihak berwenang Indonesia … untuk tidak melebih-lebihkan atau meledakkan situasi di luar proporsi”.
Dia memperingatkan hal ini “dengan mengorbankan kredibilitas otoritas Indonesia di mata publik domestik yang tertarik” dan bahwa peran opini publik adalah salah satu alasan perbedaan di antara keduanya.
“Wacana publik di Indonesia tampaknya lebih partisipatif, lebih pluralistik, yang terkadang dapat menjadi tantangan potensial bagi pemerintah,” katanya.
“Wacana publik sejauh ini tampaknya kurang menonjol di Malaysia, meskipun pihak oposisi mungkin masih mengangkat isu China dan Laut China Selatan dari waktu ke waktu selama sesi parlemen. Terus terang, wacana publik di Malaysia kurang riuh dibandingkan di Indonesia,” kata Koh.
Yang lain menyarankan perbedaan nyata mungkin bahwa Indonesia sama sekali tidak menetapkan satu kebijakan. Abuza, dari National War College, mengatakan Presiden Indonesia Joko Widodo tampaknya memiliki satu kebijakan, sementara menteri koordinator kelautannya memiliki kebijakan lain. Angkatan Bersenjata memiliki kebijakan lain, yang pada gilirannya berbeda dengan angkatan laut.
“Respons Indonesia ada di mana-mana, dan China memanfaatkan itu,” kata Abuza.
Namun, Abuza juga menganggap tanggapan negara-negara tersebut memiliki kesamaan: kekuatan militer mereka sebagian besar berbasis darat, meskipun ada peningkatan ancaman maritim. “Tidak ada negara yang memiliki sumber daya angkatan laut atau penjaga pantai mereka secara memadai, dan China mengambil keuntungan penuh dari itu,” katanya.
Aspek lain yang dapat menjadi pertimbangan kedua negara adalah sifat dari berbagai sengketa di Laut Cina Selatan. Yan Yan, direktur Research Center of Oceans Law and Policy di National Institute for South China Sea Studies, mengatakan, lokasi proyek minyak dan gas Malaysia menjadi sasaran sejumlah klaim yang tumpang tindih, yang melibatkan China, Vietnam, Malaysia, dan China. Brunei dan Filipina.
“Sebelum batas laut akhirnya diselesaikan, setiap negara memiliki klaim yurisdiksinya sendiri atas wilayah itu. Dengan demikian, pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi migas Malaysia sebenarnya merupakan tindakan sepihak di wilayah yang disengketakan,” kata Yan Yan.
Dia mengatakan sebelum masalah perbatasan diselesaikan, "tindakan sepihak dari negara penuntut di perairan yang diperebutkan merupakan pelanggaran terhadap hak kedaulatan pihak lain, yang juga dapat mempengaruhi hasil penyelesaian sengketa akhir".
“Itu sebabnya Vietnam juga mengirimkan kapal penegak hukum di sekitar rig minyak dan gas Malaysia sesekali,” kata Yan Yan.
Indonesia berada dalam posisi yang sedikit berbeda karena gagal untuk berhadapan langsung dengan Beijing terkait hak penangkapan ikan di sekitar Natuna. Pulau-pulau itu sendiri berada tepat di luar sembilan garis putus-putus yang digunakan Beijing untuk menandai klaimnya atas sekitar 90 persen Laut Cina Selatan.
Kata Yan Yan: “Bagi para nelayan Cina, daerah itu disebut 'daerah pemancingan barat daya' dan mereka sudah lama menangkap ikan di sana. Jadi menurut saya juga kurang tepat menyebut perairan itu milik Indonesia.”